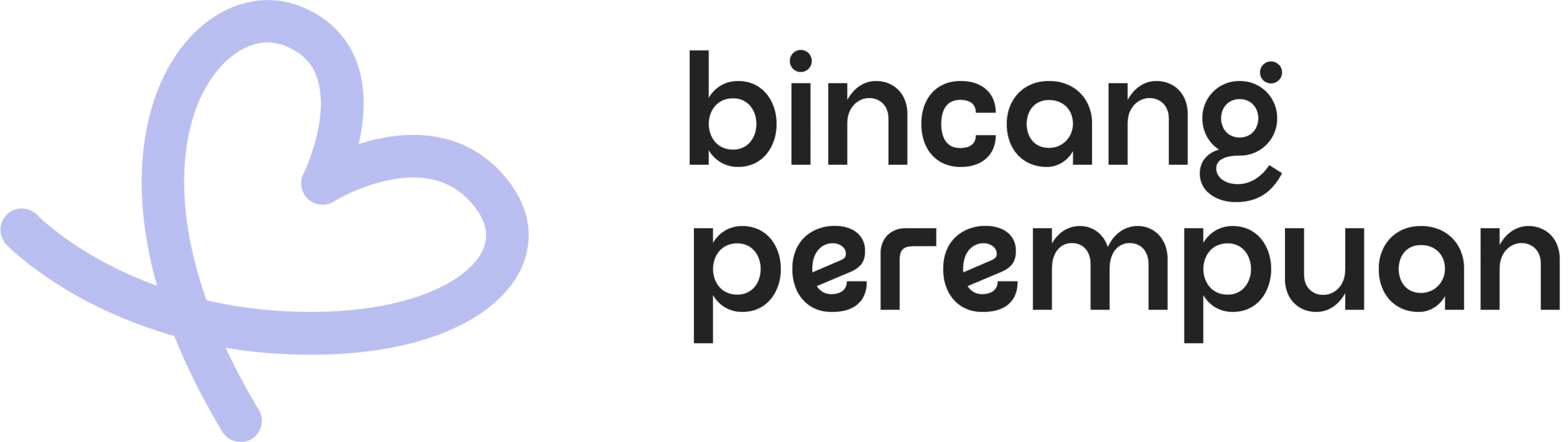Bincangperempuan.com- Siapa sih yang mau dibenci orang lain? Kedengarannya mustahil kalau hidup bahagia bisa dicapai dengan berani tidak disukai. Namun, itulah yang dibahas dalam buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga.
Buku terbitan Gramedia Pustaka ini mengupas konsep kebahagiaan melalui sudut pandang filsafat psikologi Alfred Adler. Meski tema psikologi dan filsafat terdengar berat, buku ini dikemas dalam format percakapan antara seorang filsuf dan seorang pemuda yang tengah mengalami krisis jati diri.
Meski membahas filsafat psikologi, buku ini dikemas dengan gaya yang cukup ringan. Namun, bagi yang tidak terbiasa dengan format dialog filosofis, bisa jadi terasa membosankan atau bahkan bertele-tele.
Masalah-masalah yang dialami sang pemuda terasa relevan dengan generasi muda masa kini yang kerap dirundung krisis eksistensi. Gaya bahasanya juga ringan dan mudah dipahami tanpa terlalu teoritis.
Baca juga: Setelah Dua Abad, Rafflesia Mekar di Tangan Peneliti Perempuan
Trauma Bukan Takdir, Bahagia Adalah Pilihan
Pada malam pertama diskusi, sang filsuf mengajak pemuda itu untuk mempertanyakan keberadaan trauma. Menurut psikologi Adler, trauma tidak terjadi karena sebab-akibat, melainkan karena pilihan seseorang dalam menyikapinya. Berbeda dengan teori Freud yang berlandaskan aetiologi (hubungan sebab-akibat), Adler lebih menekankan prinsip teleologi, yaitu bahwa hidup manusia ditentukan oleh tujuan dan keputusan yang diambilnya.
Dengan kata lain, seseorang tidak menjadi seperti sekarang karena masa lalunya, tetapi karena bagaimana ia memilih untuk merespons pengalaman tersebut. Begitu pula dengan kebahagiaan—bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari keputusan sadar seseorang.
Hubungan Interpersonal yang Sehat: Tidak Ada Atasan atau Bawahan
Menurut Adler, sumber utama masalah manusia berasal dari hubungan interpersonal. Ia menekankan bahwa hubungan yang sehat seharusnya bersifat horizontal, bukan vertikal. Dalam hubungan vertikal, orang cenderung melihat individu lain sebagai atasan atau bawahan, menciptakan hierarki sosial yang kaku. Sebaliknya, dalam hubungan horizontal, setiap individu dipandang setara—bukan dalam arti sama persis, tetapi dalam penghormatan terhadap nilai dan keberadaannya.
Konsep ini cukup menampar budaya senioritas yang masih kuat di banyak lingkungan, terutama dalam pendidikan dan pekerjaan. Bukan berarti anak kecil atau junior harus diperlakukan seperti orang dewasa, tetapi mereka tetap harus dihargai sebagai individu yang utuh.
Baca juga: Absennya Rumah Aman bagi Korban Kekerasan Seksual di Bengkulu
Berhenti Mengejar Pengakuan: Kamu Tidak Bisa Menyenangkan Semua Orang
Pada malam ketiga diskusi, sang filsuf membahas konsep pemisahan tugas. Salah satu poin utamanya adalah menolak hasrat untuk diakui. Mengejar pengakuan orang lain hanya akan membuat seseorang kehilangan jati diri.
Bahkan, budaya ini sudah tertanam sejak kecil melalui sistem reward-punishment di sekolah dan rumah. Anak-anak terbiasa berusaha mati-matian memenuhi ekspektasi orang tua atau guru demi mendapat penghargaan, dan takut hukuman jika gagal. Akibatnya, banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan bergantung pada validasi eksternal.
Kishimi dan Koga menekankan bahwa menjalani hidup tanpa memenuhi ekspektasi orang lain bukan berarti kita boleh bertindak sesuka hati tanpa peduli orang lain. Sebaliknya, kita perlu memahami batasan tanggung jawab kita sendiri dan membiarkan orang lain menjalankan tugasnya masing-masing.
Pembagian Tugas: Fokus pada Hal yang Bisa Kamu Kendalikan
Konsep pemisahan tugas yang ditawarkan dalam buku ini mirip dengan prinsip dikotomi kendali dalam filsafat Stoa. Sederhananya, kita hanya perlu fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita dan melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali.
Misalnya, dalam konteks pendidikan, seorang siswa bertanggung jawab atas tugas-tugas sekolahnya, sedangkan orang tua bertugas mengingatkan dan membimbing. Jika anak memilih untuk tidak mengerjakan tugasnya, itu adalah konsekuensinya sendiri. Namun, banyak orang tua yang justru ikut campur dan memaksakan kehendaknya, sehingga mengaburkan batas tanggung jawab antara orang tua dan anak.
Pepatah yang tepat menggambarkan konsep ini adalah: “Engkau bisa membawa kuda ke air, tapi tidak bisa menyuruhnya meminum air.”
Inferioritas: Menghancurkan atau Memotivasi?
Buku ini juga membahas perasaan inferior atau insecure yang sering muncul akibat perbandingan dengan orang lain. Adler menekankan bahwa perasaan inferior hanyalah asumsi subjektif seseorang. Jika digunakan dengan baik, rasa inferioritas dapat menjadi motivasi untuk berkembang.
Contoh pemikiran inferior yang sehat:
“Aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku harus bekerja lebih keras untuk sukses.”
Contoh pemikiran inferior yang merusak:
“Aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku tidak akan pernah sukses.”
Pada akhirnya, untuk hidup bahagia, seseorang harus berhenti memenuhi ekspektasi orang lain dan menerima dirinya sendiri apa adanya. Berani tidak disukai bukan berarti bersikap semaunya, tetapi memahami bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang.
Buku Berani Tidak Disukai memberikan perspektif segar tentang kebahagiaan, hubungan interpersonal, dan keberanian menjalani hidup tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Dengan memahami konsep pemisahan tugas dan hubungan horizontal, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan dan terbebas dari tekanan sosial yang tidak perlu.
Buku ini cocok untuk kamu yang sedang bimbang antara memenuhi ekspektasi orang lain atau fokus pada tujuanmu sendiri. Meskipun bukan jawaban mutlak, buku ini bisa menjadi pemicu yang bagus untuk berefleksi dan memahami diri lebih dalam.