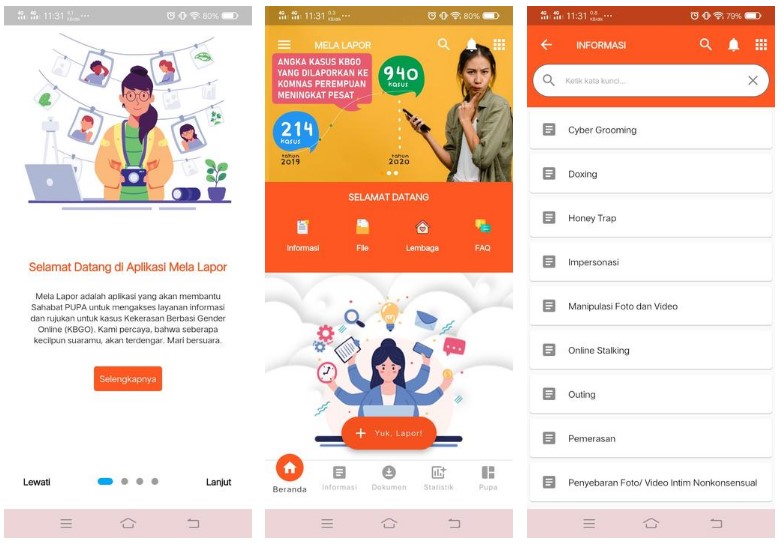“Harus. Mereka (anak-anakku–read) harus kuliah. Kalau aku dulu ngga sampe kuliah, putus sekolah. Enggak apa-apa, yang penting anak-anakku harus berpendidikan tinggi,”
Saya menemui Gia paling tidak sekali dalam sepekan, membawa balutan pakaian kotor saya sembari menerima lembar-lembar pakaian bersih dan wangi darinya. Mba Gia, begitu saya memanggilnya, Ibu dua anak ini baru memulai usaha laundrynya sendiri sekitar satu tahun yang lalu di daerah Kukusan, dekat dengan indekos mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia.
Ia selalu ramah pada setiap pelanggannya. Sesekali air mukanya terlihat lelah karena menerima terlalu banyak cucian. Namun, Gia tetap berseri-seri menceritakan suka-duka menjadi ibu yang juga bekerja (working mom) untuk membantu perekonomian keluarganya.
Kadang muncul perasaan bersalah saat Ia merasa kekurangan waktu bersama anak-anaknya karena tuntutan pekerjaan. Meski demikian, saat merasa lelah atau jenuh bekerja, ia selalu mengingat wajah anak-anaknya. Hal itu selalu menjadi jurus jitu untuk memompa kembali semangatnya agar dapat melewati hari-hari yang kadang berat dan melelahkan. Ia harus selalu ingat bahwa ia bekerja demi memberikan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya.
Tak banyak yang menyadari kekuatan perempuan untuk menjalani sejumlah peran sebagai sesuatu yang patut dikagumi dan diapresiasi secara luar biasa, setidaknya sebagaimana kita mengagumi keahlian manusia pada umumnya. Konstruksi sosial seringkali membuat kita menyepelekan beban ganda perempuan, khususnya tugas domestik sebagai sesuatu yang sudah jadi ‘kodrat’.
Meskipun saat ini telah sering dibahas tentang pentingnya berbagi tugas dalam rumah tangga, namun dalam praktiknya, pandangan yang mengakar pada peran gender tradisional membuat perempuan dianggap sebagai satu-satunya sosok yang bertanggung jawab penuh atas urusan domestik.
Alhasil, perempuan menjadi akrab dengan kerja multi peran, menjadi seorang ibu untuk anak-anak, seorang istri yang mengurus rumah tangga dan suaminya, serta seorang pekerja yang dapat memenuhi tuntutan profesionalnya. Meskipun sering merasa lelah, kadang kewalahan, perempuan tetap dituntut untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik, baik pekerjaan domestik maupun pekerjaan profesionalnya.
Hasil survei Parapuan tahun 2021 lalu terhadap perempuan dan laki-laki (234 orang) di Indonesia yang sudah menikah (29-70 tahun) menunjukkan sebanyak 64,5 persen responden mengungkapkan bahwa suami dan istri sama-sama mencari nafkah. Meskipun demikian, hampir setengah (42,3 persen) responden menyatakan tugas domestik masih lebih banyak dibebankan kepada istri.
Menyelami kisah mereka, memberikan kita cara baru untuk memaknai kekuatan perempuan. Bahwa kuat bukan hanya tentang kemampuan fisik untuk membawa puluhan kilogram beban, namun juga tentang kekuatan mental untuk dapat mengalahkan rasa lelah, jenuh, sakit, dan tetap konsisten pada tujuan mereka. Ini kisah Gia dan Lita, dituturkan secara eksklusif kepada Bincang Perempuan.
Peran Ganda: Perjuangan Seorang Ibu yang Bekerja
Gia adalah perempuan asal Tegal yang sejak menikah merantau bersama suaminya ke Depok. Bekerja di Laundry bukan kali pertama Gia bekerja. Sebelumnya ia pernah bekerja sebagai admin toko thrift daring selama dua tahun. Itu adalah pekerjaan pertamanya setelah ia berkeluarga. Kadang ia bekerja sampai malam pekat dan dingin karena harus tetap membalas pesan dan mengemas pesanan dari pelanggan meski sudah lewat jam operasional agar tidak mendapatkan komplain pelanggan.
“Sejak awal aku memang mau kerja. Pokoknya bisa sambil bantuin penghasilan keluarga. Padahal sebenarnya repot ya, saat itu anakku masih kecil-kecil, bedanya juga hanya satu tahun setengah antara anak pertama dan kedua. Aku harus suruh mereka tidur dulu, nanti kalau udah tidur, baru aku bisa tinggal kerja,” ujar Gia
Meski demikian, pekerjaan lamanya sebagai admin terbilang bisa fleksibel karena kalau tidak sedang dibutuhkan di kantor, ia boleh bekerja dari rumah sesekali. Namun, karena permasalahan khusus, kantornya yang semula di Depok dipindahkan ke Bandung. Gia sempat ragu untuk melanjutkan pekerjaannya, tak lain dan tak bukan karena ia tidak tega terlalu lama meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil di kontrakan. Saat itu anak pertamanya berada di jenjang SMP sementara anak keduanya masih SD.
“Awalnya dilema kan, terus saya izin ke anak dulu, dia sempat bingung, ‘kalau mama nggak ada nanti aku siapa yang urus?’ Jadi yang sering nangis pas kantor baru-baru mau gitu ya, aku. Akhirnya karena emang harus pindah banget kantornya, saya pindah dan anak-anak mengizinkan,” tutur Gia.
Awalnya Gia mempertahankan pekerjaannya. Ia mencoba bekerja di Bandung dengan jam kerja tiga minggu masuk, satu minggu libur. Rutinitas bolak-balik Depok-Bandung itu ternyata hanya mampu ia jalani selama tiga bulan saja. Lelah fisik tak jadi soal, masalahnya sulit bagi Gia untuk tidak mengkhawatirkan anak-anaknya saat sendirian di kontrakan jika suaminya sedang pergi bekerja.
Memutuskan berhenti dari pekerjaannya adalah pilihan yang sulit karena sejak saat itu ia kebingungan bagaimana cara membantu penghasilan suaminya
“Kalau suamiku sendirian yang kerja, gajinya nggak terlalu besar. Kurang buat sehari-hari, khususnya buat biaya sekolah anak-anak. Memang sih kalau sekolah negeri enggak bayar, tapi kan tetap butuh seragam, buku, uang jajan, dan lainnya,” jelas Gia.
Sempat ia pulang ke Tegal, berharap mendapatkan pekerjaan disana. Namun, ternyata ia tidak menemukan apa-apa. Ia memutuskan untuk menitipkan anak-anaknya kepada orang tuanya di Tegal, sementara ia kembali mencari kerja di Depok.
“Pas resign, aku bingung mau ngapain, masih ada sisa tabungan tapi lama-lama habis kalau enggak kerja. Akhirnya, sempat jual baju thrift, laku tapi pada ngutang gitu karena yang beli teman-teman. Terus, saya coba balik kampung, tapi disana mentok juga mau ngapain,” ujar Gia.
Keberuntungan menghampiri Gia saat ia mampir untuk minum di warung kopi, lalu mengobrol dengan pemilik warung kopi yang kemudian menawarkan ruko kosong yang cukup luas untuk disewakan kepada Gia. Tawaran tersebut tidak bisa ditolak. Segera ia pindah dari kontrakannya dan membangun usaha Laundrynya di ruko ini.
“Awalnya masih kepegang, lama-kelamaan penuh banget ya (cucian–read). Kalau sibuk, kadang aku jadi ngga doyan makan, yang penting kerjaan dulu. Kadang jadi hilang sendiri lapernya,” tutur Gia.
“Aku pernah lho begadang sampai jam 3 pagi. Terus nganter suami kerja jam 7 pagi, jam 8 udah mau buka laundry. Apalagi bulan puasa, tidur paling hanya tiga jam,” Gia menambahkan.
Meski diterpa pekerjaan bertubi-tubi, hal tersebut tidak mau membuatnya kehilangan waktu untuk mengobrol dan memperhatikan anak-anaknya yang sedang jauh darinya. Kadang sambil menyetrika dan melipat baju-baju, Gia menanyakan tentang makanan, sekolah, dan mendengarkan cerita keseharian mereka melalui panggilan video.
“Jadi, karena anakku jauh tiap hari video call, aku tau kalau anakku online langsung video call biarpun emaknya sibuk, aku selalu nanyain udah makan atau belum, gimana puasanya, sahurnya apa, sehari pasti dua kali video call,” tutur Gia.
Melalui telepon sang Ibu, anak-anak Gia juga bercerita tentang pelajaran di sekolah, Gia sering memberikan wejangan pendidikan kepada dua buah hatinya. Meski tak selesai sekolah menengah pertama (SMP), Ia bertekad menyekolahkan kedua anaknya sampai lulus kuliah. Gia berharap mereka mendapatkan masa depan yang lebih baik.
“Abang kamu lihat kan Mama kerjanya gimana? Susah. Jadi, mama minta kamu sekolah yang pinter, yang penting punya keahlian, jangan kayak Mama atau Bapak. Kalau punya pendidikan, kamu bisa kerja enak, santai, kalau mau usaha sendiri juga ada bekal,” demikian Gia memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar terus semangat sekolah.
Sebagai orang tua yang berniat menguliahkan anaknya, meskipun mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, Gia tetap menabung dan mempersiapkannya dengan matang-matang.
“Jadi, aku sudah punya data (untuk menguliahkan anak-anak-read) harus punya tabungan berapa dalam satu bulan. Aku rincikan sampai lulus, punya laptop di umur berapa, aku ada rinciannya semua,” jelas Gia.
Sayangnya, seorang perempuan berkeluarga yang memilih untuk bekerja seperti Gia, seringkali dianggap mengesampingkan tugasnya sebagai ibu sekaligus istri. Meski Gia sudah berusaha maksimal menjalankan perannya sebagai ibu dan istri, tetap ada stigma, sinisme, juga penyepelean terhadap peran ganda yang ia jalani.
“Mentang-mentang kerja, anak kamu tuh diurus jangan ditinggal aja kayak gitu, Jadi, ngajarin anakku yang enggak-enggak,” demikian pesan mantan istri kakak Gia yang saat ini menjadi ibu dari teman sekelas anaknya. Hubungan keluarga yang berakhir kurang baik membuat Gia juga menjadi salah satu sasaran kebenciannya.
“Kamu enak ya kerja, anakmu udah gede gede, ditinggal disono sama neneknya, disini berdua doang sama suami bisa jalan-jalan kesana kemari,” ujar Gia menirukan seseorang yang menyepelekan pekerjaannya.
Kepada Bincang Perempuan, Gia mengatakan bahwa padahal ia sendiri kesulitan untuk membagi waktu pekerjaan, waktu untuk memperhatikan anak-anaknya, waktu untuk mengurus rumah pun waktu untuk dia sendiri istirahat. Seringkali, diantara itu semua, waktu istirahatnya yang akhirnya dikorbankan.
“Orang-orang tuh enggak tahu yang saya rasain. Saya jalan-jalan juga jarang banget, paling pas suami libur dan biasanya cuma deket-deket sini doang dan enggak lama juga,” tutur Gia.
Meskipun aman, sebenarnya berat bagi Gia menitipkan anak-anaknya kepada orang tuanya. Ia sangat rindu, kadang saat bekerja pikirannya bercabang memikirkan dan mengkhawatirkan anak-anaknya yang jauh. Gia baru satu tahun menitipkan mereka di Tegal, ia berencana membawa anak-anaknya kembali ke kontrakan dan mempersiapkan pemindahan sekolah agar bisa mengurus mereka dari dekat.
“Sebenarnya saya sama sekali nggak tega ya, mereka harus nyuci sendiri, masak mie sendiri. Meskipun itu akan berguna ya pas mereka sudah dewasa, itu karena mbahnya udah sepuh juga, nggak bisa kalau semuanya dikerjain mbahnya,” ujar Gia.
Para ibu bekerja memiliki peran ganda membutuhkan mental sekuat baja. Ini tidak menegasikan berarti ibu-ibu yang memilih bekerja di sektor domestik tidak berat, karena faktanya mengurus rumah pun sama beratnya: Durasi kerja 24 jam, tanpa gaji, minim apresiasi.
Namun, saat ibu-ibu memilih tetap bekerja, mereka rentan dihantui rasa bersalah karena distigma terus-menerus, meski kenyataannya mereka selalu berusaha menjaga tugas domestik mereka sebagai ibu dan istri. Anak-anak seorang working mom dapat tumbuh sama baiknya dengan anak-anak yang ibunya berada di rumah.
Seorang working mom justru dapat memiliki waktu yang berkualitas dengan anak-anak mereka karena keterbatasan waktu mereka kebersamaan mereka. Ibu yang bekerja pun cenderung memberikan perhatian yang lebih kepada anak dan menghargai waktu yang dihabiskan bersama mereka.
Seperti Gia yang selalu menyiapkan nasi dan lauk makanan untuk anak dan suaminya, tetap mengurus segala keperluan rumah, meluangkan waktu untuk bercerita dengan anaknya, mengantar mereka sekolah dan mengaji, serta memastikan rumah dalam kondisi yang bersih. Bekerja selama lebih kurang 8 jam sehari dengan minimal 5 hari kerja. Belum lagi jika lembur, tubuh sudah dalam keadaan letih dan penat, tetapi tetap harus meluangkan waktu untuk mengurus keluarga dan rumah.
“Dia (laki-laki–read) nggak ngurusin anak, nggak ngurusin rumah, yang penting dia udah kerja, udah. Kalau kita perempuan kan beda, semuanya kan kita pegang,”
“Sekalipun pas saya sakit, saya belum makan, anak belum makan, suami lagi kerja. Kadang saking aku paksakan (untuk menyiapkan makanan-read), aku sampai jatuh pingsan,” cerita Gia.
Mendirikan Sekolah PRT agar Kerja Domestik Diakui sebagai Kerja yang Bernilai
Sebagaimana Gia, Lita yang saat ini berdomisili di Yogyakarta juga menempuh jalan yang sama terjalnya. Memutuskan mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT), Lita bagai membangun sebuah jalan panjang nan sulit di depannya.
Ia mengumpulkan para PRT di sekitarnya, mengajak mereka berserikat guna membangun kesadaran kolektif akan hak-hak mereka sebagai manusia, warga negara, dan perempuan yang seringkali direnggut dari diri mereka. Dalam masyarakat patriarki, PRT dianggap sebagai pekerjaan rendah sehingga tak jarang kasus-kasus diskriminasi, pelecehan, penganiayaan, dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi lain dilakukan oleh majikan terhadap PRT-nya.
Menurut Lita, selama ini kerja-kerja domestik tidak pernah dianggap sebagai sebuah kerja. Hal ini karena terdapat hirarki antara laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh budaya patriarki dalam masyarakat.
“Hirarki perempuan dan laki-laki berakibat pada hirarki pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Ada banyak dikotomi, misalnya pekerjaan domestik tidak dianggap bernilai, dianggap tidak membutuhkan skill karena dianggap kodrat,” tutur Lita.
“Padahal pekerjaan domestik sebenarnya pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian, tidak semua orang bisa memasak, tidak semua orang bisa membersihkan rumah, tidak semua orang bisa mengasuh anak, dan lain-lain,” tambahnya.
Menyadari keresahan ini, Lita bersedia mengorbankan segala hal yang ia punya, tenaga, pikiran, mental, bahkan materi. Mulanya, Lita bergabung dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dhien di Yogyakarta. Yayasan perempuan ini memang berfokus pada pemberdayaan perempuan, khususnya Pekerja Rumah Tangga. Tahun 2000, Lita menjadi ketua Rumpun Tjoet Njak Dhien dan menginisiasi pendidikan alternatif untuk PRT. Bersama SPRT Tunas Mulia, Rumpun Tjoet Njak Dhien mendirikan Sekolah PRT pertama kali pada tahun 2003.
“Kita ingin membongkar dan mengubah pola pikir dan struktur kultur patriarki dan itu membutuhkan upaya-upaya yang terorganisir, khususnya di bidang pendidikan. Pendidikan adalah kunci perubahan. Sekolah PRT ini dibentuk agar PRT menyadari statusnya sebagai pekerja, menyadari persoalannya sebagai pekerja domestik sehingga persoalan-persoalan mereka dapat disuarakan secara .kolektif,” tegas Lita.
Saat ini, sekolah PRT sudah ada di tujuh kota di Indonesia dan melahirkan banyak serikat-serikat PRT di berbagai daerah. Menggabungkan pendidikan kritis dan pendidikan keahlian yang dibutuhkan PRT, metode pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PRT sekaligus membongkar pemikiran tradisional tentang pekerjaan domestik.
Sekolah PRT menerapkan sistem Learning by Doing dimana setiap orang dapat menjadi guru dan murid. Kurikulumnya juga disesuaikan dengan perubahan zaman. Sekolah PRT mengajarkan literasi digital dan penggunaan teknologi, khususnya aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang pembelajaran seperti Zoom dan Youtube.
“Supaya para PRT melek digital dan bisa mengakses perkembangan pengetahuan. Artinya sekolah itu bertumbuh, media, metode, ilmunya bertumbuh, dan semuanya belajar,” tutur Lita.
Sekolah ini memunculkan para penggerak PRT yang berkenan menggerakan, menyadarkan, dan mengajak PRT lain untuk belajar di ruang ini. Disini mereka belajar bersama tentang pendidikan HAM, proteksi hukum sebagai manusia, warga negara, pekerja, dan perempuan, juga tentang serikat, advokasi, kampanye, hukum, negosiasi, dari tingkat menengah sampai tingkat lanjut
“Fasilitator bisa dari PRT-nya, bisa dari Jala PRT, atau dari aktivis tergantung konteks isu yang diangkat. Misalnya, persoalan perempuan dari aktivis perempuan, persoalan pekerja dari buruh, belajar menulis atau membuat poster dari rekan media, dan belajar paralegal dari lembaga bantuan hukum (LBH),”
Namun, perjalanan PRT untuk mengakses pendidikan tidak selalu berjalan lancar, tantangan dapat muncul baik hambatan internal maupun eksternal. Misalnya, kegiatan belajar yang diselenggarakan pada hari Minggu, namun belum semua PRT mendapatkan libur mingguan. Jika libur pun, belum tentu dapat menghadirinya, karena protes dapat datang dari mana saja, misalnya suami atau majikan.
“Rata-rata majikan tidak mengizinkan PRT sekolah karena mereka khawatir bahwa jika PRT sadar kritis mereka akan sering menuntut gitu. Jadi, ada yang beresiko kalau diberhentikan (sebagai PRT–read) jika sekolah,”
Oleh karena itu, ada PRT yang ikut secara sembunyi-sembunyi, ada yang bersedia menanggung risiko, namun sekolah PRT sendiri bersedia untuk membantu PRT-nya apabila mengalami kesulitan. Jika PRT tidak bisa datang, bahan-bahan ajar secara terbuka dibagikan ke grup untuk dipelajari kembali oleh para anggota.
Proses menuju perubahan pola pikir ini juga diadvokasikan melalui perjuangan mendapatkan payung hukum yang sah, yaitu Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Perjuangan Jala PRT bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya sudah dimulai sejak 1997 di tingkat daerah Yogyakarta yang kemudian diteruskan ke tingkat nasional.
Ssembilan belas tahun kemudian yaitu tahun 2023 ini, baru Rancangan Undang-Undang (RUU) PPRT masuk prolegnas dan saat ini sudah memasuki tahap akhir menuju pengesahan.
Sedikit yang Lita punya, yang banyak adalah keyakinan hatinya serta kekuatan dari doa dan usaha para PRT yang membawa mereka pada perjalanan sembilan belas tahun perjuangan ini. Nyatanya, doa, keyakinan, dan usaha dapat lebih dahsyat daripada gelombang waktu. Perjuangan Lita dan para PRT masih menyala dan belum berakhir.
“Sebagai pekerja, kita tidak mau mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan tidak perlu ada perbudakan. Negara harus hadir dalam memberikan support secara sistematis dalam hal perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak PRT. Hal itu akan menunjukkan bahwa negara ini negara yang ramah, berandil besar, beradab dan berkemanusiaan terhadap pekerja rumah tangga,” ujar Lita.
Kartini hampir selalu ada di sekitar kita, mungkin kita lewati saat buru-buru mengejar kereta atau saat mencari makan di pinggir kota. Perjuangan Gia sebagai ibu yang bekerja demi masa depan anak-anaknya dan Lita yang mendirikan sekolah untuk para pekerja rumah tangga adalah semangat Kartini untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Mereka adalah sosok Kartini yang luput karena masyarakat seringkali menyepelekan pekerjaan domestik serta beban ganda perempuan.
“Kan prinsipnya Kartini itu kan pendidikan menjadi kunci perubahan ya. Tidak bisa ada perubahan kalau tidak ada pendidikan. Jadi yang kita lakukan sebenarnya juga bagian dari semangat Kartini, semangat untuk memperjuangkan keadilan perempuan,” tutupnya. (Dian Amalia Ariani)