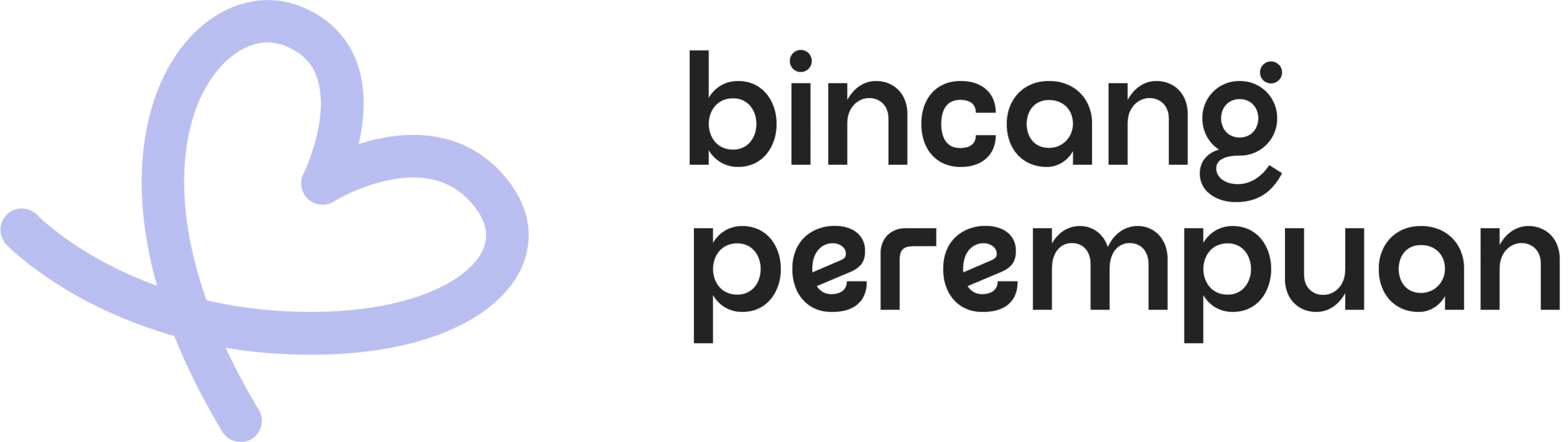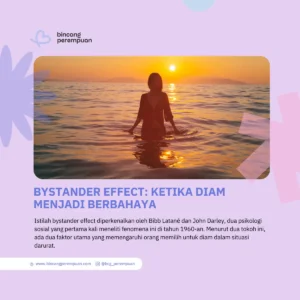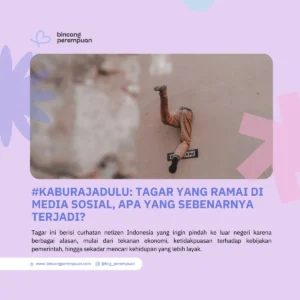Bincangperempuan.com– Keadilan bagi korban kekerasan seksual terasa begitu jauh ketika aparat penegak hukum tidak berperspektif korban. Alih-alih dilindungi dan diberikan keadilan, penanganan kasus yang tidak sensitif sering kali memperburuk trauma korban.
Akhir Januari lalu, publik digegerkan dengan pemberitaan seorang Bripda bernama Fauzan Nur Muhti, alias Bripda Fauzan, yang diterima dinas kembali setelah menikahi korban. Kasus ini bermula pada tahun 2023 silam, Fauzan dilaporkan oleh korban berinisial M, atas pemerkosaan yang dilakukannya. Laporan tersebut berujung kepada putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan sidang etik Polri.
Namun, Fauzan mengajukan banding. Dalam banding itu, ia menikahi korban, diduga agar hukumannya dapat diringankan. Banding pun diterima, sehingga sanksi terhadap Bripda Fauzan diubah hanya menjadi demosi selama 15 tahun dan penempatan khusus di Polres Toraja Utara.
Melansir Tempo, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Didik Supranoto, mengatakan bahwa pernikahan itu merupakan langkah keadilan restoratif atau restorative justice, sehingga Bripda Fauzan tidak diadili melalui mekanisme peradilan.
“Ada kesepakatan menikah, kasusnya diselesaikan kekeluargaan atau restoratif,” tuturnya, ketika diwawancarai Tempo pada Selasa, 14 Januari 2025.
Mirisnya, pernikahan tersebut nyatanya tidak memutus rantai kekerasan. Setelah menikahi korban, Bripda Fauzan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan M. Diketahui ia tidak pernah tinggal bersama dengan M. Korban pun harus mencari kamar kos di Makassar. Selama di kos, kebutuhan korban dipenuhi oleh orang tuanya sendiri, karena tidak mendapatkan nafkah yang layak dari Fauzan. Bahkan ketika M jatuh sakit pada Januari 2024, Fauzan tidak pernah menjenguknya di rumah sakit.
Penelantaran ini berdampak kepada psikis korban, ia mengalami trauma yang berat. Sempat terjadi mediasi pada Maret hingga April 2024, dengan hasil Fauzan diminta memberikan setengah dari gajinya kepada korban. Namun, perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Fauzan hanya memberikan nafkah minim yang bahkan tidak mencukupi kebutuhan hidup M.
M saat ini mesti menjalani konsultasi psikologis secara rutin untuk memulihkan kondisinya. Penelantaran yang terjadi telah menyebabkan tekanan mental dan rasa tidak aman bagi M.
Melansir Tirto, Polda Sulsel masih menyelidiki laporan KDRT dari korban dan berencana menurunkan kembali tim Propam untuk memeriksa Bripda Fauzan. Namun, belum ada kepastian kapan pemeriksaan akan dilaksanakan.
“Diperiksa Propam Polda Sulsel. (Adapun) untuk mempermudah pemeriksaan, kasusnya (KDRT) dilimpahkan ke Propam Polres Toraja Utara,” kata Didik kepada reporter Tirto, 13 Januari 2025.
Bripda Fauzan bukan satu-satunya aparat kepolisian yang terlibat di dalam kasus kekerasan berbasis gender. Berdasarkan laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tercatat ada 18 kasus kekerasan seksual oleh aparat kepolisian sepanjang Juli 2021 hingga Juni 2022.
Baca juga: Krisis Iklim Meningkatkan Risiko Kekerasan Berbasis Gender
Tepatkah Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus Kekerasan Seksual?
Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif didefinisikan sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana, yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan.
Dengan kata lain, keadilan restoratif berfokus kepada pemulihan untuk korban tindak pidana serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Bentuk-bentuk keadilan restoratif dapat berupa mediasi atau alternatif pemidanaan seperti restitusi dan pelayanan masyarakat.
Namun, penggunaan mekanisme keadilan restoratif di dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual masih menuai kontra, pasalnya keadilan restoratif sering kali justru tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Contohnya, di dalam kasus Bripda Fauzan, mekanisme keadilan restoratif ditempuh hanya untuk melepas pelaku dari jeratan hukum, dengan menikahi korban. Alih-alih mendapatkan keadilan, korban justru kembali menjadi korban kekerasan setelah menikah.
Iva Kasuma, Konsultan Hukum Akara Perempuan, menjelaskan, keadilan restoratif seharusnya berfokus pada pemulihan untuk korban, bukan peniadaan hukuman atau impunitas bagi pelaku.
“Dibukanya forum restorative justice itu justru untuk memulihkan keadilan. Jadi korban mendapatkan si pelaku meminta maaf, mengakui (kesalahannya), dan korban dengan demikian juga tervalidasi. Sekaligus akan mendapatkan pemulihan dari trauma yang dialami. Bagaimana dengan pelakunya? Apakah kemudian dia lepas? Enggak. Dia tetap akan dihukum,” jelas Iva, ketika diwawancarai oleh Bincang Perempuan pada Senin, 27 Januari 2025.
Dirinya menekankan, Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah jelas mengatur ketentuan bahwa penyelesaian perkara kekerasan seksual tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan. Menurutnya, pasal tersebut menegaskan mekanisme keadilan restoratif bukanlah perdamaian yang meniadakan hukuman bagi pelaku. Namun, aparat penegak hukum kerap menyalahartikan konsep keadilan restoratif hanya sebatas perdamaian secara kekeluargaan.
“Idealnya (keadilan restoratif) membuka ruang yang seimbang antara pelaku dan korban untuk didengarkan. Tapi, pengaturan restorative justice sekarang lebih identik dengan perdamaian, yang artinya tidak melanjutkan kasus ke proses hukum. Padahal tidak seperti itu, ada miskonsepsi soal restorative justice,” paparnya.
Iva pun menjelaskan, keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual sering tidak mempertimbangkan kebutuhan korban. “Apakah benar dia (korban) ingin dinikahkan? Apakah benar dia tidak ingin pelaku mendapatkan hukuman? Langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus dengan menikahi pelaku, itu sebetulnya pilihan yang diambil di luar kebutuhan korban sendiri,” lanjutnya.
Baca juga: Kekerasan dalam Pacaran: Fenomena yang Terus Diabaikan
Menikahkan Korban dengan Pelaku Bukan Jalan Keluar
M bukan satu-satunya korban kekerasan seksual yang dinikahkan dengan pelaku.
Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 2020, ditemukan bahwa 26,2 persen responden yang pernah mengalami kekerasan seksual memperoleh penyelesaian perkara dengan menikahi pelaku.
Fakta tersebut, tutur Iva, salah satunya disebabkan oleh pola pikir aparat yang masih menganggap pernikahan akan menguntungkan kedua belah pihak (win win solution). Sehingga kasus kekerasan seksual diselesaikan dengan menikahkan pelaku dan korban.
Sementara dari sisi korban, melansir The Conversation, acap kali terpaksa mau dinikahkan dengan pelaku karena ingin melepaskan diri dari ketakutan dan perasaan malu atas tindak pidana yang menimpa mereka. Penyebabnya, karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan seksual adalah aib.
Hal senada pun disampaikan oleh Iva. “Sementara di (masyarakat) sini, pola pikirnya adalah ‘daripada jadi aib, daripada nanti anak yang dilahirkan ini nggak punya ayah’, (jadi) lebih menebus moralitas komunitasnya dibandingkan kebutuhan korban itu sendiri,” tambah Iva.
Padahal, menikahkan korban dengan pelaku bukanlah jalan keluar. Hal tersebut dijelaskan oleh Mike Verawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia.
“Jangan hanya untuk penyelesaian, pelaku dianggap memiliki itikad baik atau bertanggung jawab karena menikahi korban. Ini tidak menyelesaikan masalah. Apalagi ketika trauma atau depresi itu masih dialami, ini justru akan berlipat-lipat ganda kekerasan yang dialami oleh korban,” jelasnya, ketika diwawancarai Bincang Perempuan pada Sabtu, 25 Januari 2025.
Menikahi korban dengan pelaku, ujar Mike, membuat korban menghadapi trauma yang berlapis, karena korban harus menjalani hidup bersama dengan pelaku kekerasan yang telah mencederai tubuh dan martabatnya, sehingga hal tersebut akan menjadi beban yang berat untuk korban.
Menurut Mike, langkah penyelesaian apa pun yang diambil, baik berupa mediasi atau sanksi administratif terhadap pelaku, tetap harus menggunakan prinsip pro korban.
Pentingnya UU TPKS dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual
Kasus Bripda Fauzan menunjukkan absennya UU TPKS dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS sudah mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual harus diselesaikan melalui proses peradilan, peraturan internal Polri belum diperbarui untuk mencerminkan aturan ini. Hal ini menyebabkan pelaku kekerasan seksual masih dapat menghindari jerat hukum melalui mekanisme keadilan restoratif.
Mekanisme keadilan restoratif saat ini diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri tidak mengatur istilah perdamaian antara korban dan pelaku. Selain itu, Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif juga menekankan bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa serta merta dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas, yakni pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak.
Oleh karena itu, kepolisian perlu memperbarui peraturan internalnya agar selaras dengan norma dalam UU TPKS serta peraturan terkait lainnya, khususnya terkait mekanisme keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual, agar keadilan bagi korban dapat terpenuhi.
“Kita sudah punya UU TPKS tapi tidak dipakai. Ini kan juga persoalan, ada apa sebenarnya? Padahal kita sudah punya UU yang sedemikian baik,” pungkas Mike.