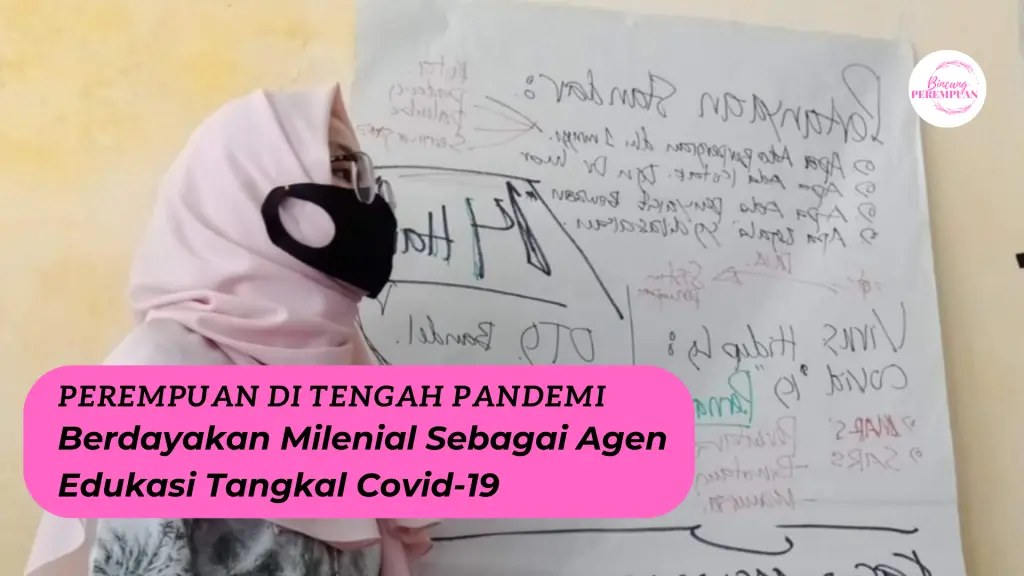“Tantangan justru datang dari pemerintah, bahkan dari akademisi. Masyarakat di sini justru mendukung kami,” ujar Olla, salah satu santri di Pesantren Al-Fatah.
Sejak berdiri pada tahun 2008, Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta telah melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan. Pesantren ini awalnya beroperasi di rumah pribadi milik Ibu Mariani, sebelum akhirnya berpindah beberapa kali.
Sejarah Berdirinya Pesantren Waria Al-Fatah
Fabiolla dan Kadita adalah dua santri yang saat ini aktif menempuh pendidikan agama di Pesantren Al-Fatah. Menurut mereka, pesantren ini lahir dari kepedulian terhadap komunitas transpuan yang kerap mengalami diskriminasi dalam beribadah.
“Setelah gempa di Yogyakarta pada tahun 2006, diadakan doa bersama lintas iman yang melibatkan berbagai komunitas. Saat itu, Ibu Mariani menyarankan, ‘Kenapa tidak dibuat pengajian saja?’ Nah, mulanya dari sana,” ujar Olla.
Sejak saat itu, pesantren berkembang di bawah asuhan Bu Shinta Ratri, seorang aktivis dan pemimpin komunitas transpuan yang berperan besar dalam mempertahankan keberadaan Al-Fatah. Di bawah kepemimpinannya, pesantren ini sempat mengalami stabilitas. Namun, situasi kembali berubah setelah beliau meninggal dunia pada tahun 2023.
Pasca-kepergiannya, pesantren menghadapi kesulitan besar dalam mencari tempat permanen. Mereka berulang kali mengalami penolakan saat hendak menyewa rumah. Stigma dan diskriminasi menjadi tembok besar yang menghalangi komunitas ini untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Banyak pemilik rumah enggan menyewakan tempatnya karena nama “waria” yang melekat pada pesantren ini.
“Beberapa kali ditolak alasannya masih khawatir kalau dibuat tempat berkumpul seperti itu, tapi akhirnya kami dapat kontrakan gitu dan semua itu dengan dana kolektif,” terang Olla menjelaskan.
Di tengah tantangan, secercah harapan tetap ada. Berbeda dari stigma yang sering dilekatkan, masyarakat sekitar justru banyak yang mendukung. Seorang ulama bahkan turut membantu mereka berbaur dengan lingkungan, memastikan bahwa keberadaan mereka tidak dianggap sebagai ancaman.
“Kami justru diterima di sini. Masyarakat mendukung, hanya pemerintah yang seakan menutup mata,” lanjutnya.
Baca juga: Representasi Perempuan di Media Masih Mencerminkan Masyarakat yang Patriarki
Menemukan Ruang Aman di Pesantren
Berbeda dari pesantren pada umumnya, Al-Fatah tidak memiliki asrama tetap bagi santri. Mereka tinggal di rumah masing-masing dan berkumpul di pesantren untuk belajar agama.
“Jadi kalau mau ibadah dan belajar bersama, kami datang ke pesantren. Ada juga Ustad Arif, seorang ulama yang aktif mengajar di sini,” jelas Dita.
Selain menjadi ruang untuk belajar agama. Al-Fatah juga menjadi ruang aman untuk beribadah tanpa rasa takut dihakimi bagi teman-teman transpuan.
Olla, misalnya, pernah mengalami penolakan saat beribadah di masjid.
“Ketika saya berada di shaf laki-laki, tapi tidak ada yang mau berdekatan dengan saya. Akhirnya, saya lebih memilih ibadah di rumah sendiri atau di pesantren,” ujarnya dengan nada getir.
Di Al-Fatah, para santri bisa menjalankan ibadah dengan nyaman. Mereka belajar mengaji, mendalami ajaran Islam, dan membangun komunitas yang saling mendukung.
Bagi mereka, hak untuk beribadah seharusnya tidak bergantung pada identitas gender. Namun, hingga kini, banyak tempat ibadah masih belum bisa menerima keberadaan mereka.
Negara Sebagai Penghalang?
Ironisnya, meskipun telah mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, tantangan terbesar justru datang dari negara. Salah satu bentuk penolakan yang mereka hadapi adalah larangan penggunaan nama yang berunsur LGBTQ+ untuk legalisasi instansi.
“Tantangan malah datang dari negara, karena tidak boleh menggunakan nama yang berunsur LGBT untuk nama instansi atau yayasan,” kata Dita.
Tidak hanya dari negara, komunitas akademik yang seharusnya menjadi ruang inklusif bagi kelompok minoritas pun tidak sepenuhnya mendukung. Seharusnya, negara hadir sebagai pelindung, bukan sebagai penghalang. Hak beragama dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tetapi dalam praktiknya, masih banyak kelompok yang mengalami diskriminasi, termasuk transpuan.
Tak hanya itu, komunitas akademik yang seharusnya menjadi ruang inklusif bagi kelompok minoritas pun tak selalu berpihak kepada mereka.
“Kemarin sempat ada pernyataan sikap dari salah satu kampus di Yogyakarta yang menolak LGBT, tapi sudah dihapus,” papar Olla.
Sikap ini menunjukkan bahwa stigma terhadap transpuan masih mengakar kuat, bahkan di lingkungan intelektual yang seharusnya menjunjung hak asasi manusia.
Baca juga: Maryam: Perempuan Minoritas dalam Bayang Diskriminasi Ganda
Tantangan dan Perjuangan yang Tak Kunjung Usai
Selain itu, pada tahun 2016, pesantren ini juga mengalami serangan dari kelompok konservatif yang menolak keberadaan mereka. Insiden tersebut menimbulkan trauma mendalam bagi para santri, yang hingga kini masih hidup dalam ketakutan akan kemungkinan serangan serupa.
Pemaksaan penutupan oleh kelompok konservatif menjadi salah satu pukulan terbesar bagi pesantren ini. Namun, komunitas tetap bertahan dengan segala keterbatasan
“Tahun 2016 itu sempat ada pelarangan dan disuruh tutup oleh FJI (Forum Jihad Islam). Untungnya jejaring dari sini banyak membantu, kami bisa kembali melanjutkan aktivitas di Al-Fatah,” kata Dita.
Hak Beragama untuk Semua Orang
Di dunia yang ideal, keberadaan pesantren seperti Al-Fatah seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Transpuan juga manusia biasa yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara yang mereka yakini.
Namun di Indonesia, perjuangan mereka untuk mendapatkan hak beragama yang setara masih panjang. Negara seharusnya berdiri di garis depan dalam melindungi hak dasar warganya, bukan malah menjadi bagian dari masalah. Pesantren Al-Fatah menjadi bukti bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kenyataan yang harus diterima dan dihormati.
Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran untuk mendukung mereka, bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam tindakan nyata—dengan membuka ruang dialog, melawan diskriminasi, dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender atau identitasnya, dapat beribadah dengan tenang.