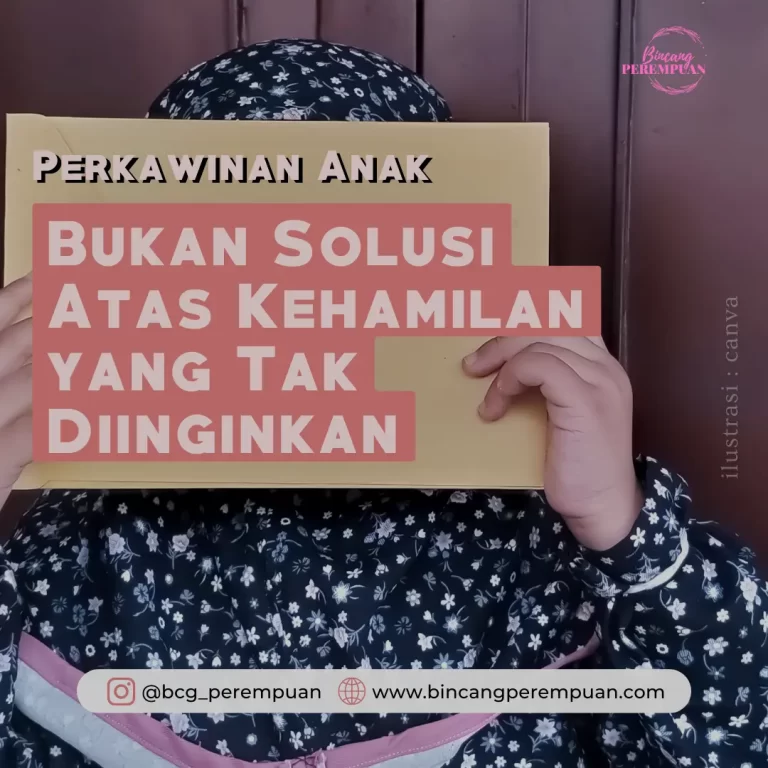Bincangperempuan.com- Pemohon dispensasi kawin terus mengalami peningkatan. Pengadilan agama, memberikan izin karena kehamilan jadi alasan. Pada tahun 2020-2022 jumlahnya mencapai 28,57%, 37,50%, dan 36,36% dari total pemohon. Tidak adanya pemantauan akan pemenuhan hak mereka setelah perkawinan membuat situasi anak-anak ini kerap memprihatinkan.
Dispensasi kawin adalah pemberian pengecualian kepada calon suami atau istri untuk melangsungkan perkawinan karena belum berusia 19 tahun. Salah satu tujuan penerapan mekanisme pengadilan ini adalah menjunjung tinggi kepentingan anak. Namun, data menunjukkan bahwa 99% perkara yang diajukan dikabulkan oleh hakim.
Risiko Perkawinan Anak
Perkawinan di bawah umur berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan. Anak yang masih bertumbuh, tetapi sudah mengalami kehamilan membuat tulangnya rawan keropos. Selain itu, memperbesar risiko melahirkan anak dengan kondisi tengkes. Secara psikologis, perkawinan anak dapat menyebabkan trauma dan krisis percaya diri. Emosi mereka tidak berkembang secara matang karena belum siap menjadi pasangan seksual, istri, sekaligus ibu.
Kepribadiannya cenderung tertutup, mudah marah, putus asa, bahkan mengasihani diri sendiri. Dengan kata lain, perkawinan anak menyebabkan gangguan kognitif. Batas umur ditetapkan sebagai indikator karena mempertimbangkan kematangan fisik maupun psikologis seseorang.
Anak yang menikah karena alasan kehamilan kondisinya jadi lebih sulit. Mereka dinilai memiliki harga diri yang rendah dan membawa aib. Seringkali disisihkan keluarga, tidak lagi melanjutkan sekolah, mengalami perundungan oleh masyarakat, dan serta-merta kehilangan teman sebaya.
Menurut penelitian, kekerasan rumah tangga banyak terjadi dalam pernikahan anak. Perempuan jadi korban dengan suami sebagai pelaku utama. Kasus kekerasan psikis paling santer terjadi, disusul dengan kekerasan fisik, dan seksual.
Salah satu yang pernah menjadi korban adalah Sukma. Ia kerap ditampar hingga dipukuli dengan beragam benda di rumahnya, seperti sabuk, pel, atau sapu. Perempuan asal Indramayu tersebut juga dilarang bergaul dengan teman-temannya. Beban kekerasan yang hampir tiap hari terjadi membuat ia menggugat cerai. Keputusan menikah ini memang lebih banyak merugikan perempuan.
Temuan itu sejalan dengan laporan statistik yang menunjukkan angka perceraian yang meningkat. Pada tahun 2021 jumlahnya mencapai 447.743 kasus. Dengan demikian, 53,50% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut laporan yang sama, kalangan istri lebih banyak menggugat cerai dibandingkan suami.
Jumlahnya mencapai 75,34%. Pertengkaran dan perselisihan jadi faktor perceraian tertinggi. Sedangkan faktor ekonomi, ditinggalkan oleh salah satu pihak, kekerasan rumah tangga, hingga poligami adalah alasan lain yang mengikuti.
Anak-Anak Adalah Korban
Perlu cara pandang berbeda dalam melihat persoalan ini. Kehamilan yang tidak diinginkan tak bisa hanya dilimpahkan sebagai kesalahan moral individu. Mengarungi perubahan biologis dan emosional jelas tak mudah. Anak-anak menghadapi dinamika seksualitas dan persetujuan batasan (consent) sekaligus berjuang untuk mengendalikan hormon mereka.
Pendidikan seksualitas jadi salah satu solusi paling konkret. Sayangnya, belum ada perubahan signifikan dalam satuan pendidikan formal. Materinya hanya sebagai selipan pada mata pelajaran Biologi atau Ilmu Pengetahuan Alam.
Pendidikan seksualitas sesungguhnya bukan hanya soal seks. Namun, senantiasa tentang komunikasi dengan guru, orang tua, atau sahabat selama proses tumbuh kembang itu. Pendidikan seksualitas meningkatkan pemahaman yang inklusif dan setara gender. Pemikiran yang menganggapnya tabu atau mempromosikan seks bebas jelas menunjukkan budaya akademik yang tertinggal.
Di sisi lain, banyak yang menyalahkan gawai atas persoalan ini. Namun, pada saat yang sama, anak-anak hanya disisakan sedikit ruang untuk bersosialisasi dan memiliki kehidupan yang sehat. Ruang-ruang publik berubah jadi perumahan dan gedung industri. Kebijakan semacam ini hanya menyisakan gawai bagi mereka. Di sinilah kehidupan anak-anak disinggungkan dengan jutaan konten pornografi. Fenomena ini bukan peristiwa organik, tetapi ketimpangan sosial bernama marginalisasi.
Dalam prinsip perlindungan anak, keburukan yang terjadi pada anak selalu disebabkan karena tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Ketika kehidupan mereka tidak optimal, pertanyaan yang seharusnya muncul adalah hak anak apa yang tidak terpenuhi? Sekali lagi, simplikasi solusi, seperti dilarang keluar malam, batasan menggunakan gawai, menggunakan pakaian tertutup jelas tidak dapat menjawab persoalan ini.
Menikah Bukan Satu-satunya Solusi
Tidak semua kehamilan mesti berujung pada pernikahan. Anak justru tidak direkomendasikan untuk menikah, apa pun alasannya. Hal ini agar mereka tidak terbebani dengan kewajiban domestik dan beban ganda.
Mereka bisa diberi tempat yang aman minim kerepotan. Anak juga bisa cuti lalu meneruskan sekolah ketika melahirkan. Dapat pula meminta pendampingan psikolog. Terlebih, untuk mencegah adanya baby blues syndrome. Fokus utamanya adalah mempersiapkan diri mereka menjadi ibu dan menjaga kesehatan anaknya.
Bagi anak yang hamil karena pemerkosaan, mereka memiliki pilihan untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini dengan syarat usia kandungan belum sampai 40 hari. Langkah aborsi ini sesuai dengan Pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Anak memiliki alasan yang lebih kuat apabila diperkosa oleh keluarga sendiri karena meningkatkan risiko kelainan genetika.
Sedangkan bagi mereka yang melakukan hubungan intim dengan persetujuan, tidak memiliki pilihan ini kecuali terdapat kedaruratan medis. Penting untuk membantu menghindarkan mereka dari aborsi ilegal karena akan mengancam diri sendiri sekaligus bayinya.
Peran keluarga dan orang terdekat sangat penting saat menghadapi kehamilan anak yang tidak diinginkan. Penting untuk menjalin komunikasi dan empati ketika menghadapi masa-masa pelik ini. Anak mesti diyakinkan bahwa orang-orang di sekitarnya merupakan ruang yang nyaman. (Delima Purnamasari)