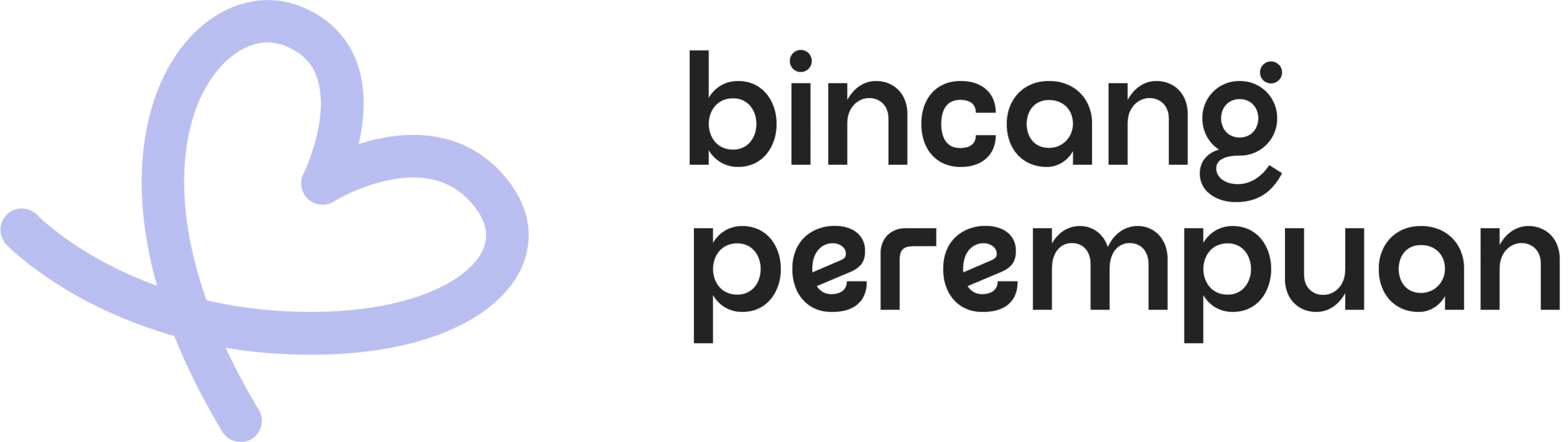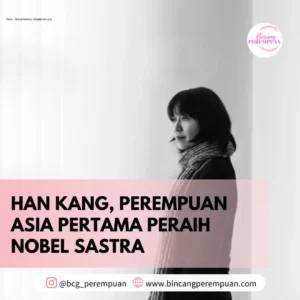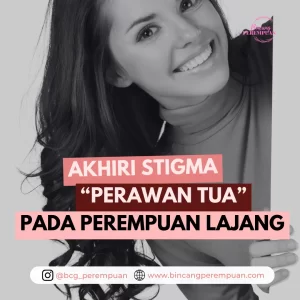“Kenapa baru lapor sekarang?”
“Dia kan nggak dipaksa…”
“Pakai baju apa waktu kejadian?”
Bincangperempuan.com– Pernah mendengar respon semacam ini? Respon tersebut menunjukkan bahwa kita belum benar-benar belajar tentang empati dan keadilan. Kita masih lebih cepat menilai korban kekerasan seksual daripada memahami keberanian mereka untuk bersuara.
Pada 9 April 2025 lalu, publik dikejutkan oleh laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan medis. Seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung diduga melakukan kekerasan seksual terhadap keluarga pasien. Tersangka, berinisial SI (31), disebut membawa korban ke lantai tujuh untuk tes darah. Korban baru menyadari adanya tindakan ganjil setelah sadar dari kondisi tidak berdayanya.
Kejadian ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja—bahkan di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman, seperti rumah sakit. Sayangnya, alih-alih mendukung korban, kita masih sering melihat komentar publik yang mempertanyakan kenapa korban tidak melawan, kenapa korban mau diajak, atau kenapa baru melapor sekarang.
Dalam konteks kasus ini, bagaimana mungkin korban bisa melawan? Pelaku adalah seorang dokter—seseorang yang memiliki legitimasi profesional dan kuasa dalam situasi tersebut. Kekuasaan ini bisa melumpuhkan, membuat korban tak punya ruang untuk berkata tidak. Maka dari itu kita tidak boleh melakukan victim blaming.
Baca juga: Ketika Kuasa Pasangan Mengancam Nyawa
Apa Itu Victim Blaming?
Victim blaming adalah tindakan menyalahkan korban atas kekerasan seksual atau pelecehan yang menimpa mereka, alih-alih memfokuskan tanggung jawab pada pelaku. Ini bisa muncul dalam bentuk komentar seperti, “Pantas dia dilecehkan, bajunya terbuka,” atau “Dia pasti menikmati karena nggak melawan.”
Menurut SACE (Sexual Assault Centre of Edmonton), victim blaming terjadi ketika seseorang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami, baik sebagian maupun seluruhnya. Dengan asumsi bahwa korban bisa “menghindari” kekerasan itu jika saja mereka bertindak berbeda.
Padahal, yang perlu kita pahami adalah kekerasan seksual bukan terjadi karena korban berpakaian tertentu, berbicara dengan cara tertentu, atau berada di tempat tertentu. Kekerasan seksual terjadi karena ada seseorang memilih untuk melakukan kekerasan. Tidak ada orang yang “meminta” untuk dilecehkan, dan tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan itu.
Relasi Kuasa: Akar Kekerasan yang Sering Diabaikan
Ternyata kekerasan seksual tidak terjadi karena hasrat semata. Lebih dari itu, ia berakar pada relasi kuasa—ketimpangan posisi antara pelaku dan korban yang menciptakan ruang dominasi dan kontrol. Kasus dokter RSHS Bandung adalah contoh nyatanya. Di mana pelaku adalah seorang profesional medis, dengan posisi otoritatif di mata pasien dan keluarganya. Dalam situasi seperti ini, korban tidak punya pilihan, bahkan untuk sekadar mengatakan “tidak”.
Data dari CATAHU 2024 Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan berbasis gender yang paling banyak dilaporkan (26,94%), diikuti kekerasan psikis (26,94%) dan fisik (26,78%). Jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat oleh mitra Komnas Perempuan mencapai 17.305 kasus—angka yang tertinggi dibanding bentuk kekerasan lainnya.
Yang menarik, data ini tidak hanya menunjukkan banyaknya kasus, tapi juga menggambarkan pola relasi kuasa yang jelas. Mayoritas korban berada pada rentang usia 18–24 tahun, sedangkan pelaku kebanyakan lebih tua atau memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Artinya, dalam banyak kasus, pelaku berada dalam posisi sosial yang lebih kuat dan lebih dominan dari korban. Komnas Perempuan bahkan menegaskan bahwa tren ini konsisten dari tahun ke tahun.
Dalam hubungan yang timpang, kuasa digunakan bukan untuk melindungi, tetapi untuk menguasai. Seperti yang dijelaskan dalam buku “Men Who Rape” oleh Groth, pemerkosaan bukan sekadar soal hasrat seksual, melainkan ekspresi dari kebutuhan untuk mengendalikan, menghukum, atau melampiaskan emosi dengan cara yang menyakitkan. Pelaku bahkan tak selalu orang asing, tetapi justru orang yang dianggap memiliki integritas atau wibawa di mata publik—guru, atasan kantor, tokoh agama, bahkan orang tua.
Relasi kuasa ini membuat korban berada dalam posisi yang sulit. Mereka mungkin takut dianggap melawan, khawatir tidak dipercaya, atau merasa tidak punya hak untuk menolak. Ketakutan itu diperparah oleh norma sosial yang menyuruh perempuan diam, menjaga nama baik, atau memaafkan demi keharmonisan.
Korban akhirnya memilih bungkam—bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka tidak merasa aman untuk melawan. Inilah kenapa victim blaming sangat berbahaya: ia mengabaikan konteks kekuasaan yang membuat korban lumpuh, dan malah menyalahkan mereka atas situasi yang tidak mereka pilih.
Lalu, Apa Respons yang Lebih Membantu?
Jika seseorang memberanikan diri untuk menceritakan pengalaman kekerasan seksualnya, dengarkan mereka dan katakan bahwa itu bukan salah mereka. Tawarkan dukungan, bukan penghakiman. Fokuslah pada langkah ke depan dan perjalanan penyembuhan korban, bukan pada mengungkit-ungkit luka yang sudah cukup dalam.
Baca juga: Series Bidaah: Potret Gelap Relasi Kuasa dalam Bingkai Iman
Kenapa Ini Penting?
Victim blaming adalah bentuk kekerasan kedua. Ia membuat korban semakin takut untuk bersuara, merasa bersalah atas hal yang seharusnya tidak mereka tanggung, dan menciptakan budaya diam yang menguntungkan pelaku.
Dalam kasus dokter ini, kita seharusnya marah bukan karena nama rumah sakit tercoreng, tapi karena ada seorang perempuan yang dilanggar hak tubuhnya, di tempat yang seharusnya menjamin keamanan dan profesionalisme.
Ketika kita memilih untuk percaya pada korban, bukan berarti kita menolak proses hukum. Tapi kita sedang membangun ruang aman, ruang yang memihak pada yang rentan, bukan pada mereka yang menyalahgunakan kuasa. Karena pada akhirnya, berpihak pada korban adalah bentuk paling dasar dari keadilan yang manusiawi.
Referensi:
- Groth, N. A. (1981). Men who rape: The psychology of the offender. New York: Springer Science.
- SACE. (n.d.). Victim blaming. Diakses dari https://www.sace.ca/learn/victim-blaming/#:~:text=Victim%20blaming%20can%20be%20defined
- Welsh Women’s Aid. (n.d.). Understanding victim blaming and why it’s harmful to survivors. Diakses 10 dari https://welshwomensaid.org.uk/news/understanding-victim-blaming-and-why-its-harmful-to-survivors