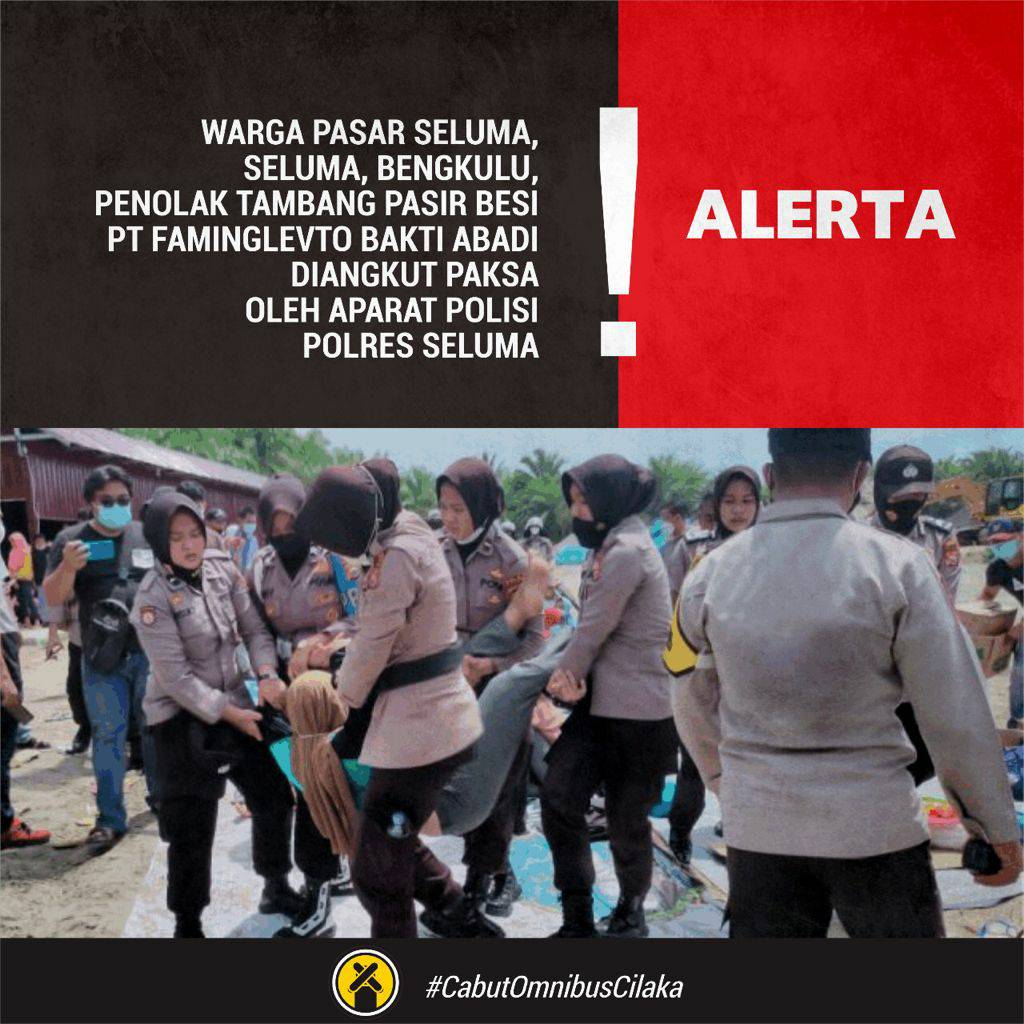Bincangperempuan.com– “Dulu tanah ini menjadi sumber penghidupan kami. Di tanah ini, saya bersama suami menanam pinang dan kelapa,” kata Sariah dengan suara lirih. Nyaris tak terdengar.
Matanya berkaca-kaca, memandang jauh ke depan mengenang kebun tersebut, sebagai warisan orang tuanya, tempat ia tumbuh dan melanjutkan kehidupan bersama suami dan anak-anaknya.
Saat ini, ia hanya bisa mengingat masa-masa “baik” itu. Sariah bercerita tentang suara angin yang melewati daun-daun kelapa di siang hari. Serta aroma khas tanah basah usai dihantam hujan.
“Hasilnya cukup untuk membiayai sekolah anak-anak, dan makan sehari-hari. Kalau panen besar atau harga pinang naik, kami bisa sedikit menabung sedikit,” kenang Sariah.
Namun, gelombang laut yang tak dapat dikontrol mengikis garis pantai Desa Pondok Kelapa sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Satu per satu pohon pinang dan kelapa tumbang. Akar-akarnya yang kokoh sudah tak sanggup lagi menahan derasnya air laut.
“Dulu sekali, air laut sampai ke batas terakhir kebun saya. Sekarang yang ada cuma air. Tidak ada lagi tanah,” ujarnya.

Hidup tanpa kebun membuat kehidupan Sariah dan keluarganya menjadi semakin sulit. Apalagi sejak kejadian itu suaminya harus bekerja serabutan hingga sakit-sakitan, dan akhirnya mengalami stroke.
Tak ada pilihan, usia yang sudah setengah abad membuat ia terpaksa mengandalkan bantuan dari anak-anaknya.
“Sekarang anak yang ngasih kami makan setiap hari. Sebenarnya saya malu kalau hanya mengandalkan anak-anak, tapi apa lagi yang bisa saya lakukan. Bapak (suami,red) juga sakit sekarang, saya harus merawatnya,” kata Sariah.
Baca juga: Rita Wati, Inspirasi Perempuan yang Memperjuangkan Hak Atas Hutan
Pekerjaan Hilang, Anak Putus Sekolah, Desa Semakin Sepi
Apa yang dialami Sariah, tak jauh berbeda dengan yang rasakan Nunung. Kehilangan tanah dan kebun serta dihimpit pandemi Covid-19 membuat hidupnya sekeluarga semakin sulit.
Nyaris tak ada harta bendanya yang tersisanya, kecuali selembar kertas yang konon merupakan bukti kepemilikan tanah, namun sekarang hanya menjadi selembar kertas yang tak ada nilai harganya.
“Kalau dulu sebelum abrasi ada tanahnya, kalau sekarang hanya tinggal sertifikat tanahnya saja yang ada,” kata Nunung dengan senyum meringis.
“Kalau tanahnya sudah tidak ada, setidaknya saya masih punya bukti bahwa tempat itu pernah ada. Itu rumah saya,” lanjut Nunung.
Bahkan, saat ini rumah sepetak yang ia tempati bersama keluarga hanya berjarak beberapa meter dari bibir sungai. Seakan tinggal menunggu waktu.
“Lihat saja, rumah itu sudah ditinggalkan penghuninya. Katanya pindah ke kota. Rumah dan tanahnya ditinggalkan saja, mau dijual tentu tak laku, pastinya sudah lebih dulu hanyut dibawa ombak,” lanjut Nunung.
Warga desa yang kehilangan tana, kebun dan sawah, lanjut Nunung terpaksa banting stir menjadi buruh dodos sawit di perusahaan swasta. Tentunya dengan upah yang jauh dari nominal biaya untuk hidup layak di Bengkulu Tengah.
“Ada yang jadi kuli bangunan, ada juga yang tukang pungut brondol sawit, yang punya modal bisa buka usaha, tapi Covid kemarin membuat kehidup disini semakin sulit,” tambahnya.
Sementara itu, Raniah, perempuan Desa Pondok Kelapa lainnya, menuturkan abrasi yang tak terelakan membuat suaminya kehilangan mata pencaharian. Tadinya, suami Raniah merupakan nelayan yang menggunakan kapal dayung.
Saban hari, sebelum matahari terbit suaminya sudah pergi melaut menyisir pantai di sepanjang Desa Pondok Kelapa. Sore hari ketika perahu mendarat, suaminya bisa membawa berkilo- kilogram aneka jenis ikan.
Ada yang langsung dijual, diolah menjadi ikan kering atau ikan asin, dan sisanya menjadi menu santap malam bersama keluarga.
Namun saat ini tak ada lagi kapal-kapal dayung yang bersandar di pantai Desa Pondok Kelapa. Suaminya pun sudah tidak melaut lagi, berganti profesi menjadi tukang potong rumput panggilan. Laut sudah melumat pantai-pantai tempat nelayan mencari ikan.
“Kalau dulu setiap bulan bisa dapat kisaran Rp4-Rp5 juta, dari jualan ikan kering, bisa untuk biaya sekolah anak. Kalau sekarang ya menunggu ada rezeki yang datang. Namun kita tetap bersyukur,” kata Raniah.

Tak hanya ancaman abrasi laut yang dihadapi Raniah dan keluarganya. Belakangan pengerukan pasir di sungai Bengkulu yang berada persis di belakang rumah Raniah kembali beroperasi setelah sempat ditutup beberapa waktu lalu.
Akibatnya erosi terjadi di dasar dan tepi sungai sehingga mengubah aliran air dan meningkatkan risiko banjir di daerah sekitar. Bila terjadi hujan berhari-hari, air sungai akan meluap.
“Hujan sehari saja, sudah naik airnya. Padahal dulu di sungai itu ada banyak kepiting dan ikan, “ lanjut Raniah.
Peliknya kondisi yang ada, dikatakan Raniah membuat desa semakin sepi. Banyak anak muda yang memilih untuk meninggalkan Desa Pondok Kelapa. Namun Raniah memilih bertahan. Bagi Raniah, meskipun sebagian tanahnya telah hilang, desa ini tetap akan menjadi rumahnya, tempat di mana ia merasa terhubung dengan akar kehidupannya.
“Banyak anak muda disini yang sekarang memilih untuk pindah ke kota. Termasuk anak saya juga, mereka suruh saya ikut, tapi saya tidak bisa,” ujar Raniah dengan tegas.
Baca juga: Maryana, Perempuan Nelayan Gurita Mendobrak Stigma
Bertanam mangrove dan menyurati pemerintah
Sariah, Nunung dan Raniah, bukan hanya mereka perempuan-perempuan yang kehilangan tanah akibat abrasi. Di banyak wilayah pesisir lainnya, cerita serupa sering terdengar. Mereka yang pernah hidup dari berkebun atau bertani kini dipaksa menjadi saksi kehilangan lahan yang diwariskan turun-temurun.
Tak ingin kondisi ini terus terjadi Raniah mengajak perempuan desa bergerak bersama dengan membentuk kelompok Perempuan Sungai Lemau. Difasilitasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu, kelompok perempuan ini mulai melakukan penananam mangrove (rhizopora) dan cemara pantai (Casuarina equisetifolia).
“Waktu itu kami sudah mulai menanam sejak tahun 2011, ini lah batang-batang cemara yang tersisa,” kata Raniah sembari menunjukan ke arah hutan cemara.
Tak cukup sebatas itu, hantaman ombak masih terus merisak area lainnya. Perempuan Sungai Lemau kembali menanami area yang terkena abrasi dengan mangrove. Menurut keterangan yang dia dapatkan, mangrove diyakini sebagai pelindung alami yang dapat mengurangi dampak abrasi.
Raniah menjelaskan, mereka telah beberapa kali menanam mangrove di area pesisir. Sayangnya, usaha mereka harus berhadapan dengan kenyataan pahit garang-nya ombak laut Samudera Hindia.
“Hari ini ditanam, besok paginya kami lihat sudah habis tersapu ombak,” ujarnya.
Tidak hanya mengandalkan aksi di lapangan, kelompok Perempuan Sungai Lemau juga mencoba menempuh jalur birokrasi. Mereka berkirim surat ke bupati, mendatangi DPRD, hingga gubernur. Mereka berharap pemerintah turun tangan untuk memberikan solusi jangka panjang.
“Kami sudah berkirim surat, beberapa kali mencoba menemui pejabat terkait, tapi sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas. Kampung kami terus tergerus, sementara bantuan konkret tidak kunjung datang,” keluhnya.
Raniah tidak menapik, beragam upaya yang sudah kelompok Perempuan Sungai Lemau lakukan tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga mematahkan semangat warga yang sudah lama berharap ada perubahan.
Meski realitanya pahit, Raniah tetap menyimpan harapan. Ia berharap pemerintah atau pihak-pihak lain dapat membantu mengatasi abrasi yang semakin mengancam kehidupan masyarakat pesisir.
“Kami tidak meminta banyak. Kalau bisa dibangun tanggul atau apapun untuk melindungi tanah yang tersisa, itu sudah cukup,” pungkas Raniah dengan nada penuh harap.
Bertahan dengan air sungai yang menguning

Abrasi pantai yang terus menggerus Desa Pondok Kelapa tidak hanya membawa dampak ekologis, tetapi juga mengubah kehidupan masyarakat setempat. Keterbatasan ekonomi dan minimnya akses terhadap air bersih membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan, meskipun risiko kesehatan mengintai.
Mereka yang tak bisa menikmati fasilitas PDAM terpaksa bergantung pada air sungai yang menguning untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci, memasak, hingga mandi. Bagi masyarakat pesisir yang tidak memiliki pekerjaan tetap biaya untuk membeli air galon tanpa merek terlalu mahal.
“Mau bagaimana lagi, air yang ada kami olah. Diendapkan dulu baru digunakan untuk mandi dan nyuci. Air galon mahal, bisa Rp5000 per galon itu untuk minum, tidak mungkin digunakan untuk mandi. Terlalu mahal, ” ungkap Umar, warga Desa Pondok Kelapa.
Dulunya, kata Umar, sungai yang menjadi sumber air desa lebarnya hanya sepanjang 6 meter, namun abrasi membuat sungai menjadi lebih lebar mencapai 50 meter.
Bila musim hujan tiba air sungai yang mereka gunakan berwarna kuning kecokelatan pekat. Ini lantaran erosi tanah yang bercampur dengan limbah domestik.
“Kami hanya bisa menyaring air itu dengan kain sebelum digunakan,” pungkasnya.
Tulisan ini merupakan bagian dari Mother Earth Project yang diproduksi dengan dukungan dari Meedan